Linguistik dipahami sebagai suatu kajian ilmiah yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik menjadi satu di antara cabang ilmu yang memiliki sifat empiris. Disebut empiris karena data yang dibahas dan dianalisis oleh linguistik adalah suatu fakta lingual yang dapat diamati di lapangan dan kebenarannya dapat diverifikasi. Empirisme bahasa yang dijadikan objek dalam linguistik itu didapat dari hasil analisis deskriptif fenomena-fenomena lingual yang terjadi pada penutur suatu bahasa tertentu. Bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa yang diujarkan manusia yang memiliki sifat alamiah dan apa adanya, tidak dibuat-buat untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial penuturnya.
Dalam ranah personal dan individual, bahasa menjadi fungsi inti bagi manusia dalam kaitannya dengan komunikasi, selain fungsi daya mengingat, persepsi, kognisi, dan emosi. Kerusakan yang terjadi pada bagian-bagian otak manusia akan menimbulkan gangguan pada kemampuan berbahasa seseorang. Ada setidaknya empat kerusakan pada bagian otak yang menimbulkan gangguan pada kemampuan bahasa seseorang, yaitu afasia, agnosia, apraksia, dan disartria (Sastra, 2011: 42).
Association Internationale Aphasie (2011) telah menyebutkan bahwa para penyandang afasia akan mengalami kesulitan dalam banyak hal. Hal-hal yang dimaksud merupakan sesuatu yang biasa terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam hal komunikasi, seperti melakukan percakapan; berbicara dalam grup atau lingkungan yang gaduh; membaca buku, koran, majalah atau papan petunjuk di jalan raya; pemahaman akan lelucon atau menceritakan lelucon; mengikuti program di televisi atau radio; menulis surat atau mengisi formulir, bertelepon, berhitung, mengingat angka, atau berurusan dengan uang; juga menyebutkan namanya sendiri atau nama-nama anggota keluarga. Penyandang afasia mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa, tetapi mereka bukanlah orang yang tidak waras.
Dalam hubungannya dengan kompetensi berbahasa, afasia dipahami sebagai gejala atau gangguan yang terjadi pada kemampuan berbahasa seseorang yang diakibatkan oleh kerusakan pada korteks (Sastra, 2011: 42). Afasia tidak terjadi pada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki sistem bahasa tertentu. Maksudnya adalah afasia hanya akan terjadi pada seseorang yang sebelumnya sudah memiliki sistem bahasa tertentu. Senada dengan apa yang diungkapkan Sastra, Kusmoputro (1999: 22) juga menyatakan bahwa afasia sebagai salah satu gangguan kebahasaan seseorang (baik lisan maupun tulis) yang disebabkan oleh gangguan atau kerusakan pada bagian otak. Dari kedua definisi di atas, jelaslah bahwa afasia merupakan gejala patologi bahasa pada diri seseorang yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada satu di antara bagian-bagian otak. Kerusakan otak itu sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit, tetapi yang paling sering diakibatkan oleh penyakit gangguan peredaran darah di otak dan cedera otak (strok dan trauma) (Yunus, 1999:3).
Dalam hubungannya dengan ranah psikologis, para penyandang afasia kerap memandang dirinya berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya gejala kesulitan melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat mudah untuk dilakukan oleh mereka. Pada praktiknya, para penyandang afasia akan bersusah-payah dan sangat memerlukan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat mudah mereka lakukan. Kondisi ini semakin membuat mereka merasa kurang percaya diri dalam menjalani proses komunikasi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Manifestasi fisiologis yang ada pada para penyandang afasia juga sangat berbeda dengan orang-orang normal. Oleh karenanya, dukungan dari berbagai pihak terhadap mereka akan sangat membantu dalam proses terapisnya, inilah suatu hal yang sangat penting bagi mereka. Setidaknya, dengan adanya intensitas komunikasi dan sosialisasi dengan para penyandang lainnya akan menjadikannya kembali percaya diri. Bahkan, antarpenyandang afasia akan dapat saling memahami satu sama lain tanpa kata-kata. Kondisi inilah yang kerap kali kita temukan pada proses terapi penyembuhan para penyandang afasia di beberapa rumah sakit. Para terapis wicara klien afasia mencoba untuk memosisikan dirinya sangat dekat dengan para penyandang afasia sehingga kedekatan emosional dan psikologis dirasa akan mampu mempercepat proses penyembuhan penyakit tersebut.
Bahasa tidaklah dikelola oleh seluruh hemisfer kiri otak manusia (Pinker, 1994: 307). Kondisi demikian telah lama dipahami oleh para ahli, tepatnya setelah Paul Piere Broca memublikasikan hasil telaahnya terhadap satu di antara pasien rumah sakit yang ada pada tahun 1861. Dalam publikasinya, Broca menyatakan bahwa pasiennya yang mengalami gangguan tertentu pada hemisfer bagian kiri otaknya telah mengalami gangguan pada kemampuan wicaranya. Pada realisasi bahasanya, pasien mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi-bunyi bahasa; tidak seperti sedia kala. Tidak berselang lama dari penemuan Broca, Wernicke dan Jules Dejerine telah mempertegas teori Broca. Berbagai temuan yang dipubliaksikan dari gejala patologi bahasa ini telah membuktikan adanya kaitan yang erat antara otak manusia dan kemampuan berbahasa.
Kaitan antara otak manusia dan kemampuan berbahasa ini pun pada akhirnya menarik perhatian para tokoh dari disiplin lain di luar dunia kedokteran untuk menekuninya. Jakobson (1971) dan Lecours, Lhermitte, dan Bryans telah mencatat bahwa pendekatan multidisipliner terhadap patologi bahasa yang disebut afasia ini pertama kali dilakukan oleh Th. Alajouanin, A. Ombredane, dan Marguerite Durand pada tahun 1939. Pada awalnya mereka menekuni kecenderungan adanya penyederhanaan (improverishment) pola-pola bunyi yang ada pada para penyandang afasia. Seiring perkembangannya, kajian-kajian yang menjadikan hubungan antara otak manusia dan kemampuan berbahasa sebagai objeknya terus dilakukan.
Kajian yang mengangkat masalah perilaku bahasa para penyandang afasia menjadi satu di antara topik pengamatan bidang interdisipliner yang disebut neurolinguistik. Interdisipliner tersebut lebih menekankan pada masalah bagaimana bahasa direpresentasikan dan diproduksi oleh otak manusia. Dalam hubungannya dengan upaya menemukan pola, sistem, dan struktur otak manusia yang mendasari penggunaan bahasa, neurolinguistik menggunakan dua macam cara. Pertama adalah mengamati perilaku bahasa para penyandang gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh ketimpangan pada otaknya. Kedua adalah dengan cara mengamati proses berbahasa pada otak subjek normal dengan batuan berbagai alat (Kridalaksana, 1993).

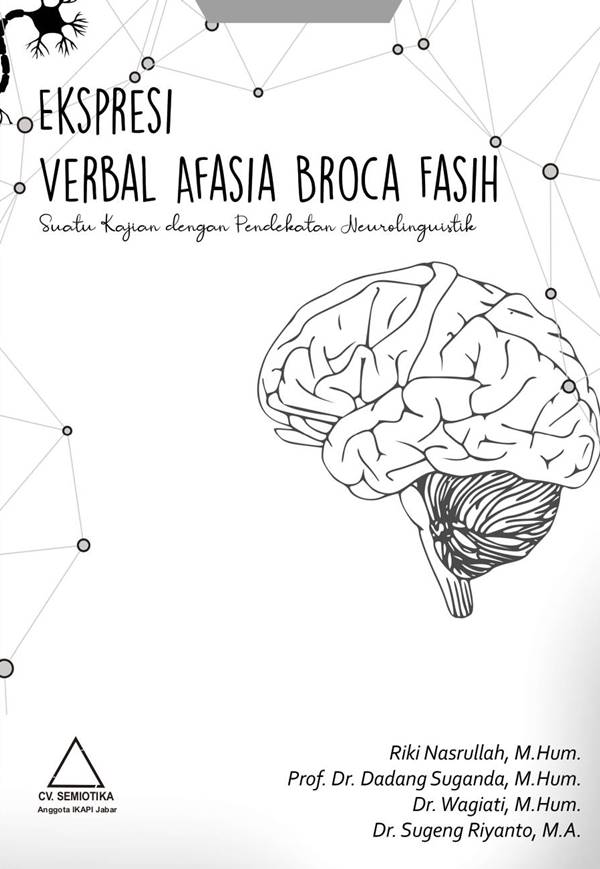
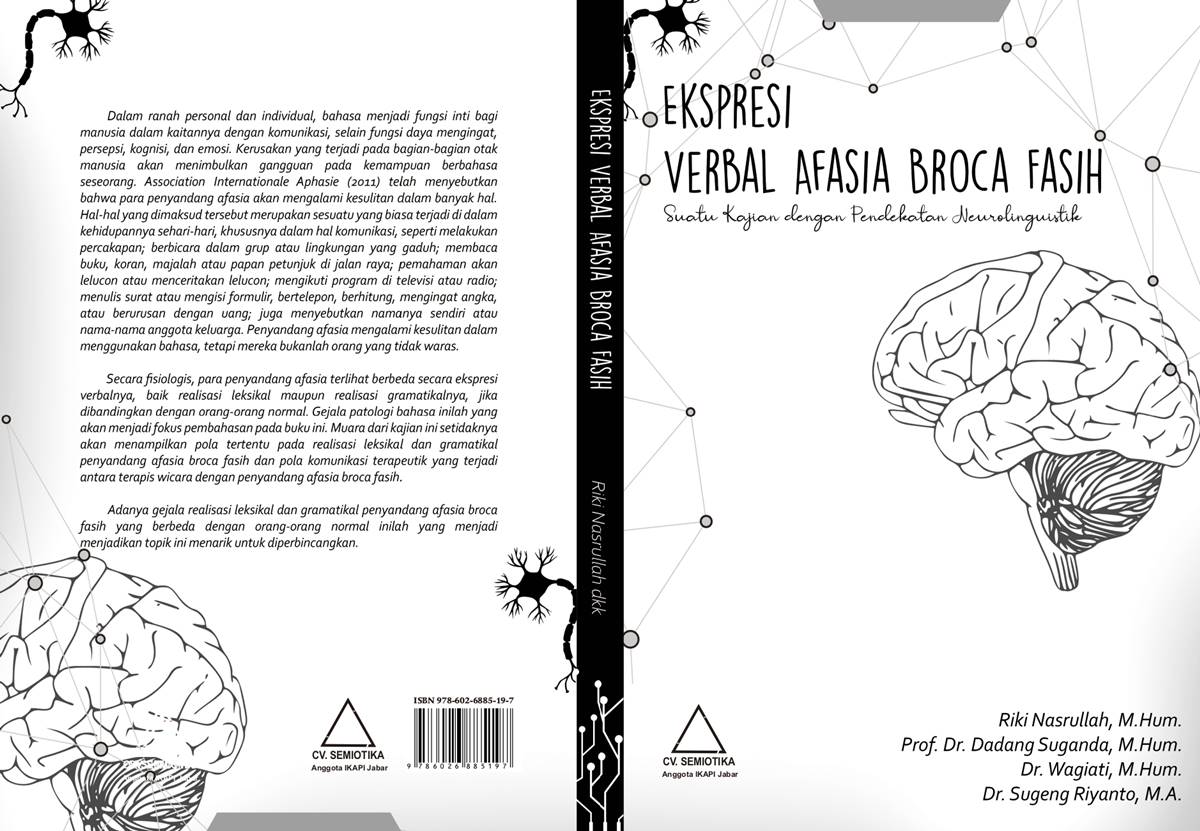

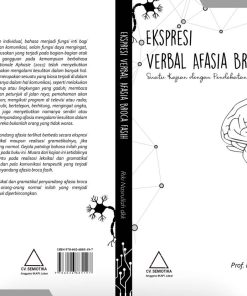



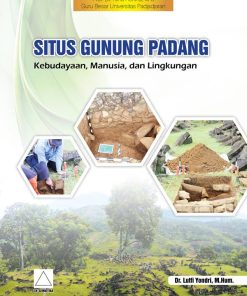

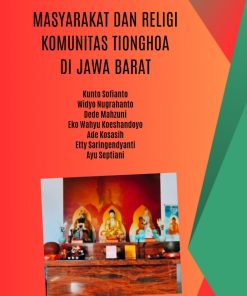

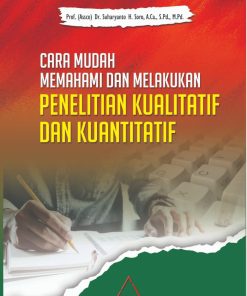

Ulasan
Belum ada ulasan.